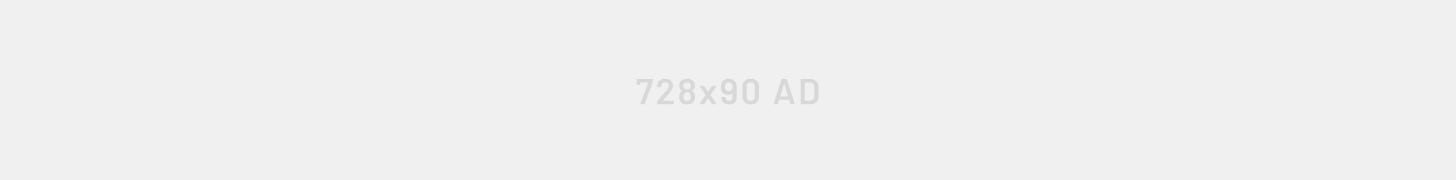INDONESIANINSIGHT – Dunia kini terbelah di bawah bayang-bayang arsitektur geopolitik baru yang digagas oleh Donald J. Trump melalui entitas ambisius bertajuk Board of Peace. Sejak diumumkan secara resmi, organisasi ini telah memicu fragmentasi diplomatik yang tajam, di mana garis pemisah antara negara yang memilih untuk bersinergi dan mereka yang menarik diri secara elegan menjadi semakin kontras.
Di tengah ketidakpastian tata kelola global, Dewan Perdamaian muncul bukan sekadar sebagai mediator konflik di Gaza, melainkan sebagai ujian bagi loyalitas dan kemandirian prinsip luar negeri bangsa-bangsa di hadapan pengaruh unilateral Amerika Serikat.
Eksistensi Dewan Perdamaian berakar pada visi Trump untuk menciptakan “perdamaian melalui kekuatan” (peace through strength) yang melampaui birokrasi tradisional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Meskipun secara legal merujuk pada Resolusi UNSC 2803, piagam organisasi ini dirancang dengan struktur korporatif yang ketat, menuntut kontribusi finansial sebesar 1 miliar dolar bagi keanggotaan permanen.
Hal inilah yang memicu perdebatan mengenai apakah lembaga ini merupakan bentuk altruisme global atau justru sebuah upaya sistematis untuk memprivatisasi perdamaian dunia di bawah kendali tunggal sang Ketua Pendiri.
Peta Aliansi dan Penolakan
Hingga Januari 2026, arus kekuatan dunia terbagi ke dalam dua kutub utama. Di satu sisi, terdapat kelompok negara yang telah memberikan komitmen penuh untuk bergabung, yang mencakup sekutu strategis di Timur Tengah serta beberapa kekuatan ekonomi berkembang.
Indonesia, bersama dengan Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Yordania, dan Pakistan, menjadi barisan utama yang melihat dewan ini sebagai pragmatisme politik demi stabilisasi kawasan. Selain itu, negara-negara seperti Argentina, Hungaria, Maroko, Vietnam, Uzbekistan, hingga Azerbaijan turut merapat dalam orbit pengaruh ini.
Sebaliknya, sebuah benteng resistensi mulai terbangun kokoh di Eropa. Negara-negara dengan tradisi diplomasi multilateral yang kuat secara tegas menolak undangan tersebut.
Prancis, di bawah kepemimpinan Emmanuel Macron, menjadi pelopor penolakan dengan alasan menjaga integritas kedaulatan Uni Eropa dari tekanan koersi ekonomi. Langkah ini diikuti secara konsisten oleh Norwegia, Swedia, dan Slovenia, sementara Jerman dan Italia menunjukkan sikap skeptis yang mendalam. Sebuah perpecahan transatlantik yang mengingatkan kita pada era perang dingin namun dalam balutan persaingan pengaruh ekonomi.
Menyikapi fenomena ini, Kementerian Luar Negeri RI melalui pernyataan resminya menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia adalah manifestasi dari upaya proaktif dalam penyelesaian konflik Palestina.
Namun tantangan besar datang dari suara-suara di benua biru, sumber dari Istana Élysée menyebutkan bahwa ancaman tarif dan isu Greenland telah melukai kepercayaan diplomatic yang membuat inisiatif ini sulit diterima secara moral. Donald Trump sendiri, melalui kanal resminya, menegaskan bahwa mereka yang menolak hanya akan “tertinggal dari sejarah” sementara Dewan Perdamaian terus melaju melakukan rekonstruksi di daerah konflik.
Peta dunia kini tak lagi hanya digambar oleh batas wilayah, melainkan oleh tanda tangan di atas piagam dewan yang penuh kontroversi ini. Kehadiran negara-negara besar dalam barisan anggota maupun barisan penolak adalah cermin dari dunia yang tengah mencari bentuk keseimbangan baru.
Di akhir hari, perdamaian yang sejati tidak seharusnya menjadi hak eksklusif mereka yang mampu membayar, namun merupakan janji suci bagi kemanusiaan yang harus dijunjung tanpa syarat, melampaui kepentingan sempit faksi-faksi politik dunia.